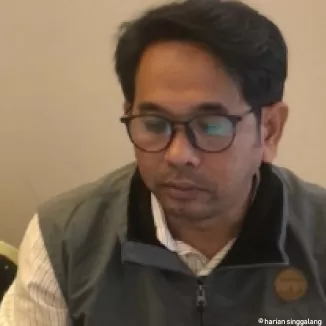Dr. Zulkifli, M.A.(Mudir Ma’had al-Jami’ah Tuanku Imam Bonjol, UIN Imam Bonjol Padang)
Wujud implementatif meramadhankan jiwa berada pada titik jiwa yang bersyukur (baca: ‘abdan syakura). Kondisi ini ditandai dengan jiwa yang senantiasa menerima segala nikmat Allah dalam bentuk dan kondisi apapun, serta mengingat-Nya dalam rangka mendistribusikan dan memanfaatkannya, baik dalam bentuk ibadah maupun beramal shaleh. Dalam konteks ini, Imam al-Ghazali menegaskan rasa syukur mesti terefleksi dalam bentuk keselarasan komponen jiwa, lisan, perbuatan untuk memelihara nikmat dari segala bentuk kefasidan dalam rangka memuji-Nya.Bahkan secara konseptual, Imam al-Sanusiy mendefinisikan kata syukur dengan ungkapan: segala bentuk sanjungan (pujian) terhadap Zat yang patut untuk disanjung disebabkan keindahan sifat-Nya, baik dari aspek Maha Pemberi Karunia maupun aspek Maha Kesempurnaan yang dimiliki-Nya. Atas dasar itu, tiada satupun yang terjadi di atas bumi ini kecuali atas izin dan kehendak Allah Swt. yang mesti atau wajib disyukuri.
Salah satu yang mesti disyukuri adalah keberadaan bulan Ramadhan. Bulan ini menjadi momentum bagi umat Islam untuk melatih rasa syukur yang terhunjam di dalam jiwa. Dalam hal ini, umat Islam menunaikan ibadah puasa sebagai bagian dari instrumen pembersihan jiwa yang beririsan dengan aktivitas jiwa yang senantiasa beristighfar dan berdzikir. Kendati demikian, momentum yang dirindukan itu (kesucian jiwa) tidak memiliki arti ketika nilai syukur belum bergeser dan berbingkai kesabaran bagi shaimin. Kondisi ini menjadi suatu keniscayaan karena puasa membentuk nilai kesabaran. Ketika pelaksanaan ibadah puasa tidak mampu menumbuh-kembangkan rasa sabar di dalam diri, maka ibadah puasa gagal menjadi instrumen pembersihan jiwa. Akhirnya, puasa yang dilaksanakan hanya sebatas aktivitas berlapar-lapar dan berhaus-haus sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dalam rentang waktu satu bulan.Imam al-Ghazali menegaskan bahwa makna sabar adalah kondisi jiwa yang kokoh untuk melaksanakan tuntutan agama dalam rangka menghadapi bujuk rayuan hawa nafsu. Dalam hal ini, Imam al-Ghazali menempatkan hawa nafsu sebagai sesuatu yang dahsyat menghancurkan kehidupan manusia. Kecenderungan nafsu mengantarkan manusia ke ranah merasa ‘ujub atau membanggakan diri sendiri (riya’). Bahkan, hawa nafsu cenderung mendorong manusia untuk memasuki ranah kedengkian (hasad) ataupun ranah fitnah agar memperoleh kedudukan yang mulia di mata manusia, memperoleh harta demi kelangsungan hidup, ataupun sejenisnya. Hal ini pada dasarnya menyengsarakan diri sendiri bahkan orang lain. Atas dasar itu, dorongan hawa nafsu hanya dapat dibendung dengan nilai kesabaran yang terhunjam di dalam jiwa karena hawa nafsu tidak saja membunuh dua atau tiga nyawa, bahkan dapat menghancurkan dunia.
Menilik lebih dalam terkait dampak yang ditimbulkan oleh rayuan hawa nafsu, Rasulullah Saw. mengingatkan para sahabat dan seluruh umat manusia melalui peristiwa perang Badar. Ketika umat Islam memperoleh kemenangan dalam perang Badar, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa kita baru saja kembali dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Sahabatpun heran, seraya bertanya kepada Rasulullah: apakah perang yang lebih besar dari perang ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: perang yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Petikan hadits Nabi ini menggambarkan secara gamblang bahwa keberadaan hawa nafsu menjadi sesuatu yang mesti dihadapi dengan penuh kesabaran. Sabar (menahan diri) dari melaksanakan ibadah umrah yang kesekian kalinya –sebagai contoh– pada saat tetanga sebelah rumah tidak memiliki biaya untuk menebusi hutang; tetangga tidak memiliki makanan untuk dimakan; biaya yang dibutuhkan untuk modal bertahan hidup, ataupun contoh sejenisnya. Sekiranya ibadah haji setiap tahun ataupun umrah diwajibkan setiap saat, pastilah Rasulullah manusia pertama yang menunaikan ibadah tersebut setiap tahun dan setiap ada kesempatan. Tetapi kenyataannya, Rasulullah menjawab pertanyaan para sahabat: ibadah haji wajib ditunaikan satu kali –pada saat memenuhi syaratnya– seumur hidup manusia.Di sisi yang sama, Imam Ali bin Abi Thalib menggambarkan pembuhulan nilai kesabaran dengan keimanan seseorang melalui sebuah ungkapan: ketahuilah bahwa pembuhulan (kaitan) antara kesabaran dengan keimanan bagaikan kepala dengan tubuh. Jika kepala manusia (keimanan) seseorang sudah tiada, secara otomatis tubuhnya tidak akan berfungsi. Begitu juga sebaliknya, apabila tubuh manusia (kesabaran) sudah hilang, maka keimanan seseorang akan hilang. Ungkapan ini menegaskan tentang pentingnya kesabaran di dalam kehidupan manusia.Kendati demikian, Imam al-Ghazali mengklasifikasikan wujud kesabaran yang mesti dibangun di dalam jiwa berdasarkan hukumnya, yaitu: pertama, sabar terhadap segala sesuatu yang dilarang syariat hukumnya adalah wajib, seperti menahan diri (sabar) dari untuk melakukan kemaksiatan menjadi sesuatu yang wajib bagi manusia; kedua, sabar terhadap segala sesuatu yang makruh menurut syariat hukumnya adalah sunnah, seperti sabar dari memakan sesuatu yang membuat bau mulut (jengkol atau sejenisnya); ketiga, sabar terhadap segala yang membahayakan jiwa diri sendiri ataupun orang lain hukumnya haram, seperti melanjutkan ibadah shalat yang di dalam waktu bersamaan terlihat seorang anak kecil yang didekati ular berbisa dengan potensi anak kecil tersebut bisa saja digigitnya. Kendati nilai kesabaran sangat berkaitan dengan keimanan, namun sesuatu yang lebih penting di dalam tatanan amal ibadah maupun amal shaleh, yaitu keikhlasan. Tiada arti seluruh amalan yang dilakukan tanpa didasarkan kepada niat yang ikhlas.Tutur keikhlasan senantiasa menjadi komitmen setiap umat Islam pada saat menunaikan ibadah shalat. Pernyataan iftitah itu dapat diterjemahkan: sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Sederhananya, Gus Ulil merefleksikan makna ikhlas itu dengan meniadakan pamrih duniawi yang berasal dari manusia dalam beribadah serta hanya mengharapkan pamrih ukhrawi dari Allah saja. Bahkan, keberadaan nilai ikhlas menjadi ruh dari setiap amal ibadah dan amal shaleh yang dikerjakan manusia. Hal ini diungkapkan Imam Ibnu ‘Atha’illah melalui kata hikmahnya: setiap amalan yang dilaksanakan manusia hanyalah wujud nyata (baca: jasad), sementara wujud halusnya (baca: ruhnya) adalah terpatrinya sir keikhlasan di dalam setiap amalan tersebut. Atas dasar itu, kewajiban menunaikan ibadah puasa mesti didasarkan kepada nilai keikhlasan. Sekiranya dilaksanakan hanya sebatas penunaian kewajiban sebagaimana pada umumnya (puasa masyarakat ‘awam), maka tidak memiliki arti untuk mensucikan jiwa dari setiap bentuk noda dosa dan kesalahan yang selama ini terjadi.
Wujud akhir pencapaian kesucian jiwa melalui ibadah puasa Ramadhan (baca: ghufira lahu maa taqaddama min dzanbih) mesti dibangun dari permintaan maaf serta kemaafan dari setiap kawan dan lawan di dalam kehidupan. Hal ini berlanjut dengan permohonan ampunan kepada Allah melalui hati yang senantiasa beristighfar sekaligus senantiasa berdzikir setiap saat dan dimanapun berada. Pencapaian puncak istighfar serta dzikir akan mengantarkan umat Islam ke ranah mensyukuri seluruh garis takdir yang Allah tetapkan. Kondisi ini membutuhkan nilai kesabaran di dalam menerima dan menghadapi setiap ketentuan tersebut. Bahkan, seluruh bentuk amalan itu hanya bisa membekasi dalam mensucikan jiwa pada saat terpatri keikhlasan di dalam jiwa umat Islam. Dalam konteks ini, capaian akhir yang diharapkan melalui ibadah puasa adalah keikhlasan. Atas dasar itu, kehadiran bulan Ramadhan semestinya menggeser nilai syukur dan nilai kesabaran menjadi nilai keikhlasan di dalam jiwa sebagai wujud implementatif dari nilai ketaqwaan.Wallahu a’lam bi al-shawab!!!