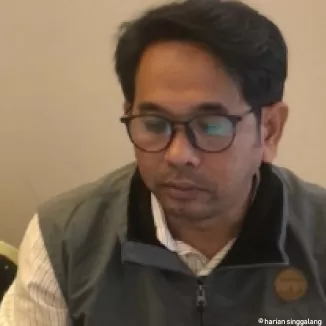Fadhila Humaira
Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah merupakan falsafah hidup orang Minangkabau hasil dari kesepakatan tokoh-tokoh adat dan para ulama zaman dulu. Kesepakatan itu tertuang dalam Piagam Sumpah Satie Bukik Marapalam di awal abad ke-19. Namun dalam proses kelahirannya, bermula dengan terjadinya pertentangan antar kedua belah pihak, hingga sempat melewati konflik bersenjata yang melelahkan. Namun sejarah membuktikan, hasil kesepakatan yang bijak itu telah memberikan peluang tumbuh dan berkembangnya beberapa angkatan ”generasi emas” selama lebih satu abad berikutnya. Dalam periode keemasan itu, Minangkabau dikenal sebagai lumbung penghasil tokoh dan pemimpin. Baik dari kalangan alim ulama maupun dari kalangan cendekiawan pemikir dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka terbukti mampu berkiprah di tataran nusantara bahkan menembus dunia internasional. Mereka itulah ujung tombak kebangkitan budaya dan politik bangsa Indonesia pada awal abad ke 20, termasuk dalam upaya kemerdekaan bangsa ini dari tangan penjajah pada pertengahan abad 20. Sebagai satu kelompok suku kaum yang jumlah penduduknya sangat kecil, yakni kurang dari 3% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Namun peran kunci yang telah dimainkan oleh sejumlah tokoh-tokoh besar dan elit pemimpin Minangkabau zaman dulu, telah membuat keterwakilan urang awak dalam kancah perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia terasa melebihi (over-represented). Sejarah mencatat dan tak dapat dipungkiri, bahwa Minangkabau, walaupun sebagai kelompok etnis kecil, tapi pernah berada di puncak piramida bangsa, baik dilihat dari sudut budaya, ekonomi maupun politik. Putera-puteri terbaik Minangkabau pernah menjadi pembawa obor peradaban (suluah bendang) bangsa besar Indonesia ini. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) merupakan gabungan ajaran adat dan agama, yang mana dalam pelaksanaannya adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Secara sederhana dapat diartikan bahwa adat Minangkabau itu berdasarkan agama Islam dan agama Islam sendiri dasarnya adalah Al-Qur’an (Kitabullah). Sebagai contoh pemanfaatannya, tentu akan sangat bagus sekali jika para konselor menjadikan ABS-SBK sebagai salah satu landasan ketika melakukan bimbingan dan konseling. Dengan demikian, falsafah ini benar-benar menjadi sebuah nilai integrasi antara agama dan budaya, karena keduanya tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang Minangkabau (Yuhaldi, 2022). Konsep ABS SBK tidak terlepas dari konsep Minangkabau yang dapat diterjemahkan ke dalam banyak arti, antara lain adat Minangkabau, kerajaan Minangkabau, bahasa Minangkabau, masyarakat Minangkabau, termasuk letak geografis Minangkabau (Albert et al., 2022). Namun dalam tulisan ini, definisi Minangkabau ini lebih dititikberatkan pada dimensi sosio-kultural daripada dimensi geografis atau regional. Dari segi sosial budaya, menurut Khoiriyah (2022) penamaan alam Minangkabau adalah cerminan kecintaan orang Minang terhadap alamnya. Sedangkan filosofi 'alam takambang jadi guru' adalah ungkapan keterikatan masyarakat dengan alamnya. Di sisi lain, Albert et al (2022) menyatakan bahwa kehidupan masyarakat Minangkabau itu berdasarkan ajaran Islam. Dengan kata lain, orang Minangkabau wajib beragama Islam, jika tidak, itu artinya bukan orang Minangkabau. Selanjutnya, istilah ABS-SBK memiliki makna dan arti yang sangat luas dan dalam. Ia tidak hanya sekedar makna kembali ke surau. Namun, untuk memahami falsafah ini secara luas dan mendalam, diperlukan diskusi akademik dengan kehadiran para tokoh-tokoh terkait, yakni kelompok pimpinan tradisi Minangkabau yang dikenal sebagai tigo tali sapilin, tungku tigo sajarangan. Mereka adalah niniak mamak, cadiak pandai dan alim ulama. Niniak mamak dari bagian adatnya, cadiak pandai dari kaum akademisinya, dan alim ulama dari para tokoh Islam (Yuhaldi, 2022). Albert et al (20220 menambahkan bahwa zaman dulu ABS-SBK merupakan landasan kuat dalam membangun lingkungan sosial budaya Minangkabau, dan terbukti mampu melahirkan kelompok manusia unggul dan tercerahkan. Falsafah ini dapat diibaratkan sebagai ”Surau Kito”, yakni tempat pembinaan ”anak nagari” yang ditumbuh-kembangkan menjadi sarana pambangkik batang tarandam, nan pandai manapiak mato padang, nan bagak manantang mato ari, jo nan abeh malawan dunia urang, dan di akhiraik masuak Sarugo. Namun, kutiko jalan lah dialiah urang lalu dan kacang lah lupo jo kuliknyo, maka robohlah Surau Kito. Begitulah kira-kira gambaran nasib dengan peran yang kini berada di tangan etnis Minangkabau. Suara kita hanyalah sekadar sayuik-sayuik sampai saja, bahkan nyaris tak terdengar. Nampaknya kita perlu bertanya kepada Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Sapilin: Baa ko kini Angku Pangulu? Baa ko kini Buya kami? Baa ko kini Cadiak Pandai (pemerintah) kami? Mengutip Jeanne Cuisinier, Joko Darmawan (2017) menulis, Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama (kaum Padri) terhadap kaum adat yang mempunyai kebiasaan berjudi, sabung ayam, minuman keras, sampai kepada hal-hal substansi terkait matrilineal, matriakat dan warisan sesuai adat Minangkabau. Padri ingin mengubah semua kebiasaan dan hukum adat tersebut. Zulkifli & Salim Ampera (2005) menyebutkan, tahun 1815 perselisihan itu mencapai puncaknya. Kaum Padri dipimpin Tuanku Pasaman menyerang pusat Kerajaan Pagaruyung yang menjadi basis kaum adat. Serangan tersebut membuat Yang Dipertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah mengungsi ke Lubuk Jambi. Pada 21 Februari 1821, karena kekalahan tersebut, salah satu petinggi Pagaruyung Sultan Tangkal Alam Bagagar datang ke Padang meminta bantuan Belanda dan menandatangani perjanjian dengan Residen Belanda, James du Puy. Pada tengah hari 4 Maret 1822, serdadu Belanda dengan kekuatan sekitar 400 infanteri dan artileri menyerbu Pagaruyung. Di bawah pimpinan Letkol A. T. Raaff mereka berhasil menduduki Pagaruyung dan daerah-daerah lainnya di sebelah Tenggara Tanah Datar. Menurut Dobbin (1992) Belanda telah melakukan persiapan penyerangan tersebut sejak Februari 1822. Joko Darmawan (2017) juga mengungkapkan, serbuan yang direncanakan dengan matang itu berhasil memukul mundur kekuatan Padri keluar dari wilayah Pagaruyung. Setelah menguasai Tanah Datar, Raaff dan pasukannya membangun benteng dinamakan Fort Van der Capellen. Mengiambil nama Godert Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen, seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bertugas sebagai pimpinan tertinggi ke-41 wilayah koloni sejak 1816-1826. Raaff sendiri merupakan perwira muda berusia belum genap 28 tahun ketika itu. Raaff dan pasukannya tak berhenti sampai di situ, setelah menaklukkan Pagaruyung, lalu mereka menyerang Lintau dan wilayah lainnya yang dikuasai Padri. Padri mndur dari Batusangkar dan Pagaruyung, tapi bukan berarti kalah, mereka menyusun kekuatan di Lintau, sekitar 37 kilometer dari Benteng Fort Van der Capellen. Seterusnya menurut Joko Darmawan, Padri melakukan serangan balasan pada 10 Juni 1822, menghadang pergerakan pasukan Raaff di Tanjung Alam, tapi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Namun serangan berikutnya pada 14 Agustus 1822 Padri berhasil. Dalam pertempuran di Baso, seorang perwira Belanda Kapten Goffinet menderita luka berat, dan kemudian meninggal pada 5 September 1822. Akibat serangan pasukan Padri di bawah pimpinan Tuanku Nan Renceh itu, Belanda mundur kembali ke Batusangkar. Pada 13 April 1823, pasukan Raaff kembali menyerang Lintau, tapi gagal karena perlawanan sengit Padri. Belanda kembali ke Batusangkar pada 16 April. Setelah Belanda menguasai Pagaruyung sejak 1821, Yang Dipertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah kembali pada 1824. Namun, setahun kemudian ia wafat. Letkol Raaff sendiri, setelah berhasil menguasai Pagaruyung diangkat menjadi Residen Padang pada 1823. Namun, ia meninggal dunia mendadak pada 1824 setelah sakit panas. Walaupun sudah menguasai menguasai Pagaruyung, sementara itu di luar Belanda semakin kewalahan dengan perlawanan Padri. Akhirnya pada 15 November 1825, Belanda menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Padri, saat itu pimpinan Padri sudah berada di tangan Tuanku Imam Bonjol. Selama masa gencatan senjata itu, Belanda berkonsentrasi menghadapi Perang Diponegoro yang sedang berkecamuk di Pulau Jawa sejak 1825-1830. Darmawan menulis, Padri sendiri saat jeda perang itu memulihkan kekuatan dengan merangkul kaum adat. Perbedaan antara syariat Islam dan adat Minangkabau diselesaikan dengan ‘Plakat Puncak Pato’ di Bukit Marapalam. Dari sinilah terwujud konsensus Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah itu yang hingga kini tetap dipakai masyarakat Minangkabau. Bahagian kedua Perang Padri berlanjut pasca Perang Diponegoro, adalah saat bersatunya Kaum Padri dan Kaum Adat melawan Tentara Hindia Belanda, yang juga memakan waktu yang panjang dan menelan banyak korban. Jeffrey Hadler (2010) mengatakan, pada titik inilah Perang Padri beralih dari yang sebelumnya perang saudara antara reformis Muslim dengan tradisionalis adat, lalu kemudian berubah menjadi perang melawan pendudukan kolonial. Disimpulkan bahwa falsafah ABS-SBK adalah suatu prinsip hidup yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Prinsip ini mencerminkan pendekatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada nilai-nilai adat (budaya lokal) yang selaras dengan ajaran Islam. Artinya, tradisi atau adat istiadat setempat harus sesuai dengan hukum Islam, yang bersumber dari Alquran. Hal ini mencerminkan semangat untuk memadukan nilai-nilai lokal dan agama Islam, sehingga tradisi dan adat istiadat setempat diarahkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Ide ini juga bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara tradisi lokal dan norma-norma Islam tanpa adanya bertentangan satu sama lain. Prinsip ABS-SBK adalah pertanda pentingnya menyelaraskan kehidupan masyarakat dengan ajaran agama dan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ini mencerminkan semangat harmoni antara budaya lokal dan agama Islam, dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Penting untuk dicatat bahwa prinsip ini mencerminkan dinamika dan keseimbangan antara lokalitas dan universalitas, antara identitas budaya dan agama. Penerapan prinsip ini juga dapat dilihat dalam berbagai bentuk, tergantung pada interpretasi dan konteks setempat dalam masyarakat Minangkabau. (Penulis Mahasiswa S2 PAI, UIN Bukittinggi)Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

hariansinggalang.co.id
Opini lainnya
Isral Naska
Harapan pada Anggota DPD Terpilih
Harapan pada Anggota DPD Terpilih
eriandi
Musim Panas dan Kebakaran
Musim Panas dan Kebakaran
Septri Andelvita
Mewujudkan "Nagari Maju Agam Maju" Melalui Aplikasi Smart Nagari
Mewujudkan "Nagari Maju Agam Maju" Melalui Aplikasi Smart Nagari
Otong Rosadi
Batas Usia Pensiun Polri Diubah, Untuk Siapa?
Batas Usia Pensiun Polri Diubah, Untuk Siapa?
Rahmad Fajral Ilhami
Mahasiswa Kedokteran Unand Temukan Terapi Kanker Payudara Berbasis Misel Polimer
Mahasiswa Kedokteran Unand Temukan Terapi Kanker Payudara Berbasis Misel Polimer