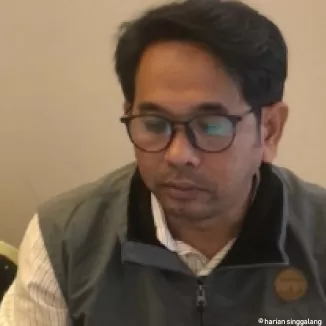Banyak keprihatinan muncul atas fenomena terus merosotnya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya di DPRD Sumbar. Banyak pihak menuding bahwa ketidakmunculan perempuan di panggung politik ini sebagai kelemahan gerakan kesadaran gender. Mungkin aktifis gender di Sumatera Barat sedang atau sudah lelah, demikian bisik-bising ‘sarkas’ acap terdengar di warung kopi.Ketimbang menegakkan benang basah dan berdalih bahwa panggung politik bukan satu-satunya tempat bagi perempuan untuk berkiprah, saya memilih untuk menerima tudingan-tudingan dan keprihatinan yang terlontar dari ‘warung kopi’ sebagai masukan. Pilihan ini berangkat dari kesadaran bahwa memang representasi itu satu alat politik utama yang akan dibaca oleh masyarakat dan memberikan efek serta pesan guna mempengaruhi opini dan menimbulkan aksi. Kalau dalam politik saja tidak terwakili, bagaimana dalam kesehariannya?
Berdasarkan data di KPU, untuk periode 2019-2024 ini jumlah anggota DPRD perempuan hanya 4 orang dari 64 orang anggota. Belakangan ditambah 2 orang sebagai pengganti antar waktu (PAW). Jumlah itu menurun dari periode sebelumnya, 7 orang. Namun tetap saja jauh dari angka keterwakilan yang sudah ditetapkan oleh negara, 30 persen atau sekitar 21 orang. Menariknya, fenomena ini dibaca oleh pihak KPU sebagai bentuk kurang nya upaya caleg perempuan dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat pemilih, isu-isu yang dibawa tidak dikemas dengan baik dan sosialisasi program tidak dilakukan. Padahal, menurut mereka, pihak KPU sudah memberi ruang yang cukup lebar bagi perempuan (Antara, 14/8/2019)).Menurut saya, rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen bukan karena tidak bekerjanya perempuan di level bawah. Ini hanya persoalan teknis. Siapa yang mengoyak panggung ketika kampanye kalau bukan perempuan? Siapa yang membagi-bagikan kaos, menghidupkan program sehat di posyandu, gerak jalan, bagi-bagi sembako dan sebagainya? Yang menjadi soal adalah pada level strategis terutama dimulai dalam partai sendiri. Sudahkah dipatuhi aturan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik harus memenuhi target penyertaan 30 persen perempuan (Pasal 2 Ayat 2 dan 5 UU No 2/2011). Hulu persoalan ini harus dibenahi. Ini tentu saja bukan perkara kuantitas semata tetapi perkara kualitas. Sehingga harus dikaji dengan bijaksana, kenapa aturan ini dibuat, bahwa partai bukan hanya milik ‘pemilik’ nya. Siapapun pemilik partai, maka 30 persennya adalah perempuan. Setiap perempuan di negara ini berhak menempati posisi yang sudah disediakan, tanpa syarat. Karena itu partai harus benar-benar menjamin hal ini.
Keluhan yang sering saya dengar – lagi-lagi dari ‘warung kopi’, adalah sulitnya mengajak perempuan untuk terlibat dalam partai politik, sehingga langkah paling pragmatis bagi pemilik partai atau elit partai dilevel yang lebih rendah, adalah dengan main ‘comot’ nama. Asal nama perempuan, sehingga proses pengajuannya diterima di KPU. Inilah kemudian yang massif terjadi, langkah paling praktis dan mudah. Soal kualitas, suara, keterwakilan gagasan, itu semua tidak dipikirkan benar demi persyaratan administratif semata.Tentu saja perlu benar kita sadari bahwa politik adalah soal kekuasaan dan patriarki juga satu model bagaimana kekuasaan dijalankan oleh laki-laki. Setelah serangkaian pertarungan panjang, sehingga menjadi habit atau membudaya, akan dengan ikhlaskah laki-laki menyerahkan kekuasaannya atau membaginya dengan adil kepada perempuan? Bagi saya ini bukan soal memohon untuk difasilitasi atau diberi kesempatan, tapi bagaimana bertarung agar sama-sama bisa mendapat kesempatan menjalankan kekuasaan di negara ini dengan setara. Ini amanat demokrasi yang harus kita tunaikan bersama sebagai warga negara. Toh pada akhirnya kita bukan semata-mata ingin menegakkan ‘kerajaan’ masing-masing, kita tidak sedang menuju negara oligarki, kita bukan bagian dari oligark-oligark yang terus membangun menara gadingnya tapi kita berpolitik untuk ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’, bukan?
Sudah saatnya bangsa ini menyadari bahwa Budaya patriarkis dalam politik itu buruk dan tidak perlu dipertahankan. Bahwa laki-laki lebih tahu, lebih lihai, lebih menguasai strategi atau lebih punya banyak uang, ini tidak benar, ini bias. Bagaimanapun, kenyataan ini masih ada dan masih kuat membelenggu pemikiran masyarakat. Ada kegamangan bagi perempuan untuk masuk ke dunia politik karena bias-bias pemikiran serta ‘rumor’ politik yang berkembang. Bahwa dunia politik itu dunia laki-laki, keras, penuh intrik dan fitnah. Memasang baliho di tengah kota, berteriak-terik untuk minta dipilih, mengklain diri paling hebat dan paling banyak berbuat untuk rakyat atau menjanji-janjikan sesuatu yang belum pasti, semuanya juga dipandang sebagai bukan ‘perangai’ yang terpuji, tetapi harus dilakukan oleh seorang politisi.Padahal sesungguhnya apa yang biasa dipertontonkan oleh politisi selama ini, seperti menebar janji, menebar baliho atau membangun citra diri di ruang-ruang publik, itu semua hanyalah strategi –yang karena berhasil kemudian ditiru pula oleh mereka yang ingin memenangkan kontestasi. Di sisi lain, strategi-strategi seperti itu bertentangan dengan kebanyakan watak feminis terutama perempuan. Kaum perempuan, terutama di Minangkabau memang dibesarkan dengan berbagai aturan tabu (sumbang duo baleh salah satunya). Aturan-aturan tabu berupa nilai moral dan nilai etik tersebut kemudian menjadi belenggu. Karena itulah, menurut hemat saya, banyak perempuan memilih untuk tidak berpolitik praktis atau membutakan matanya pada persoalan-persoalan politik.Perempuan Masuk PolitikPerempuan Masuk Politik (PMP) adalah bagian dari gerakan pendidikan politik bagi kaum perempuan untuk memberantas penyakit ‘buta politik’. Gagasan ini muncul atas dasar kesadaran bahwa perempuan adalah subjek pembangunan. Perempuan bukan objek yang terus dihitung sebagai korban—dan angkanya terus dipolitisasi untuk mempertahankan status quo kekuasaan.
Buta politik (atau pura npura buta) merupakan penyakit sosial yang berbahaya. Mereka yang mengalaminya tidak sadar (pura-pura tidak sadar) bahwa kemiskinan, pelecehan seksual, putus sekolah, stunting, mahalnya harga-harga barang, sulitnya mendapat layanan kesehatan semua itu berhubungan dengan keputusan politik bukan takdir tuhan semata.Untuk memutus mata rantai kekuasaan oligarki, patriarkis dan demi tegaknya demokrasi di negara ini, perempuan-perempuan harus dimampukan dalam menyelesaikan problemnya sendiri melalui jalur ilmu pengetahuan bukan Bantuan Langsung Tunai semata. Perempuan harus diberi ruang seluas-luasnya dalam memasuki dunia politik salah satu nya dengan jalan menyediakan sekolah-sekolah khusus yang mengajarkan pendidikan politik. Dengan begitu kehadiran perempuan dalam kontestasi politik tidak lagi sebatas tukang sorak, pelengkap suara atau pengurus urusan-urusan non strategis namun benar-benar ikut bertarung dan berjuang atas dasar kesadaran kritis yang sudah terbangun lewat proses pendidikan.
Untuk itu, ide ini perlu dieksekusi secepatnya. Saya membayangkan akan berdiri lembaga-lembaga politik ‘jalanan’ di seluruh sudut-sudut nagari di Sumbar ini, dimana perempuan berkumpul dan bersama membangun kesadaran untuk membuka mata dan berhenti berpura-pura buta. Semoga.(***)